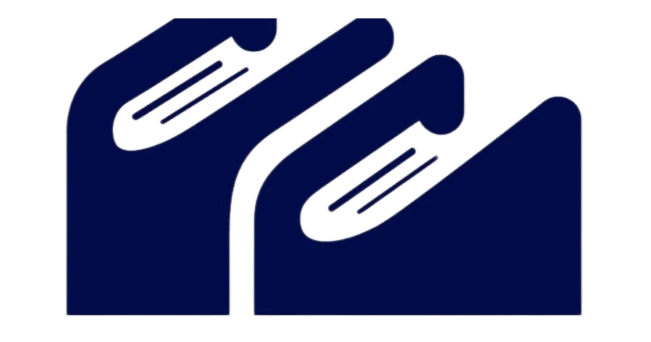Oleh: Alexander Aur
Perlu, tapi kurang laku. Singkat saja gambaran buku-buku filsafat di negeri kita.
Apa pasal? Hal itu sesuai dengan adagium: Primum manducare, deinde philosophari. Makan dahulu, berfilsafat kemudian. Bahwa buku-buku filsafat belum menjadi kebutuhan, itu merupakan cermin sebagian masyarakat kita yang masih bergelut soal perut.
Salah satu hal menarik dalam dunia perbukuan di Indonesia adalah keberadaan buku filsafat. Buku filsafat perlu, tetapi tampaknya kurang laku. Bagaimana masa depannya di Indonesia? Pemetaan keberadaan buku filsafat berikut ini dapat menjadi jalan masuk untuk menakar masa depan buku filsafat di Indonesia.
Sekurang-kurangnya ada empat gelombang keberadaan buku filsafat di Indonesia. Pertama, gelombang akademik. Kedua, gelombang gerakan sosial. Ketiga, gelombang penerbitan formal.
Pada gelombang pertama, buku filsafat beredar di kalangan kampus, khususnya kampus filsafat dan fakultas filsafat. Kampus filsafat didominasi oleh kampus-kampus berbasis agama. Misalnya, di lingkungan agama Katolik, sejak tahun 1963 didirikan beberapa Sekolah Tinggi Filsafat di beberapa tempat di Indonesia.
Fenomena menarik terjadi di lingkungan agama Islam. Banyak Institut Agama Islam Negeri yang membuka program studi filsafat. Beberapa universitas negeri pun membuka fakultas filsafat.
Sebagai contoh buku-buku filsafat gelombang pertama ini adalah Filsafat sana-sini(I. R. Poedjawijatna, Yayasan Kanisius, 1975) dan Soerjanto Poespowardojo dan K. Bertens (ed.) berjudul Sekitar Manusia. Menyusul yang lebih sistematis karya-karya Harry Hamersma, Magnis Suseno, dan K. Bertens.
Buku filsafat yang beredar pada gelombang pertama ini, diterbitkan oleh penerbit-penerbit luar negeri. Bahasanya pun bervariatif: Inggris, Jeman, Prancis, Arab, Spanyol, dan Italia. Para mahasiswafilsafat harus menguasai bahasa asing, supaya bisa mengakses gagasan-gagasan filosofis dari buku filsafat.
Ruang lingkup peredaran buku filsafat meluas ke masyarakat di luar kampus pada gelombang kedua. Hal itu seiring dengan perubahan konstelasi kekuasaan politik dan situasi sosial di Indonesia tahun 1995-an.Misalnya di Yogyakarta, sekitar 1995-an (menjelang Gerakan Mahasiswa 1998) banyak mahasiswa aktivis menerbitkan buku filsafat secara clandestin dan tak ber-ISBN.
Materi buku tersebut merupakan hasil ramuan dari kuliah-kuliah filsafat di kampus-kampus seperti UGM, IAIN Sunan Kalijaga, dan Universitas Sanata Dharma. Ruang lingkup peredarannya pun masih sangat terbatas. Hanya di kalangan mahasiswa aktivis. Hal ini wajar karena pemerintah Orde Baru sangat keta menyensor buku-buku filsafat.
Menyusul keruntuhan kekukasaan Orde Baru, kebebasan pers dan kebebasan mengemukakan pendapat pun mendapat ruang ekspresinya. Bersamaan dengan euforia kebebasan itu, lahirlah banyak sekali penerbit baru hampir di seluruh Indonesia. Di Yogyakarta, sebagai contoh kasus, banyak penerbit buku didirikan. Inilah gelombang ketiga sekitar tahun 2000-an.
Buku filsafat yang diterbitkan merupakan terjemahan dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Para akademisi filsafat, aktivis sosial-politik, dan pro-demokrasi ramai-ramai menulis buku filsafat dan diterbitkan oleh penerbit-penerbit baru tersebut.Dengan mudah pula para peminat dan pembaca memperoleh buku filsafat di toko-toko buku maupun di pasar-pasar buku loak. Diskusi dan bedah buku filsafat pun diselenggarakan di berbagai tempat.
Pada gelombang ketiga ini, filsafat, gagasan-gagasan filosofis, dan buku-buku filsafat seperti menjadi sebuah gaya hidup. Dalam diskusi, seminar, atau tulisan di koran, terasa tidak afdol bila tidak mengutip gagasan dari filsuf tertentu.
Fenomena orang yang membeli dan menenteng buku filsafat menyingkapkan gaya “intelektual” dalam dirinya, meskipun mungkin saja terbata-bata mencerna gagasan filosofis dalam buku yang ditentengnya.
Tetapi ada satu persoalan terkait buku filsafat terjemahan.Kualitas terjemahannya tidak cukup baik. Hal itu disebabkan oleh para penerjamahnya, bukan orang-orang yang belajar filsafat secara formal. Para penerjemah hanya bermodalkan kemampuan berbahasa Inggris atau Jerman. Padahal, dalam menerjemahkan buku filsafat,penerjemah harus mengerti sistem berpikir dari filsuf dan pemikiran filsuf lain yang diacu oleh filsuf yang bukunya diterjemahkan.
Tanpa kemampuan-kemampuan itu, sebuah buku filsafat hasil terjemahan tidak lebih dari sebuah pengkhianatan secara ugal-ugalan terhadap pemikiran para filsuf. Alih-alih pembaca dapat memperoleh gagasan filosofis para filsuf dalam buku filsafat hasil terjemahan, pembaca justru memperoleh kekaburan gagasan filosofis.
Kehadiran pustaka fisafat, yang demikian itu (santai, populer) adalah tonggak tersendiri. Yang berhasil membumikan fisafat. Keluar dari cangkang “seram” yang mengerutkan dahi membacanya. Alhasil, penjualan bukunya pun terbilang lumayan.
Saat ini, penerbitan buku filsafat oleh penerbit-penerbit, baik penerbit kecil maupun penerbit besar, masih terus berlangsung. Tentunya, dengan jumlah yang berfariasi. Bahkan ada beberapa penerbit yang menerbitkan buku filsafat sejumlah yang dibutuhkan oleh pembaca. Artinya, ada permintaan dari pembaca atau institusi terlebih dahulu, baru diterbitkan. Hal ini yang disebut penerbitan dengan pola print on demand.
Pertanyaan akhir untuk pembaca, bagaimana “nasib” buku filsafat di Indonesia pada masa depan? Dari paparan singkat di atas, kita bisa memperkirakan bahwa “nasib”buku filsafat di Indonesia pada masa depan, belum banyak berubah: perlu tetapi kurang laku.
Lingkup peredaran buku filsafat masih di kalangan terbatas. Selama bangsa ini masih belum menyadari bahwa peradaban dan wajah masa depan Indonesia juga terletak pada cara berpikir warganya, maka “nasib” buku filsafat pun masih menempuh jalan sunyi. Atau bisa jadi, buku filsafat memang harus menempuh jalan sunyi, seperti filsuf yang menempuh jalan sunyi untuk menghasilkan gagasan filosofis.
Selanjutnya supaya buku filsafat diterima masyarakat luas dan menentukan arah dan wajah bangsa ini ke depan, penerbit-penerbit buku perlu berkreasi dalam mengemas isi dan memasarkannya. Tanpa itu, buku filsafat tetap dalam jalan sunyinya sendiri.
Kini buku-buku filsafat banyak terbit dan beredar, seiring kebutuhan zaman. Sebagai induk segala ilmu, buku filsafat semakin bervariasi dan tersegmentasi. Ada filsafat ilmu sebagai kapita selekta kuliah. Ada filsafat ilmu komunikasi. Ada filsafat etika. Filsafat pendidikan. Bahkan, filsafat Pancasila. Kebanyakan adalah buku teks, atau buku ajar di perguruan tinggi, semisal karya I Gede Pasek Eka Wisanjaya, Filsafat Hukum.
Di pihak lain, kita juga menemukan buku fisafat yang “makin membumi”. Semisal karya Prof. Armada, Mgr. Dr. Valentinus Saeng, Prof. Djohansjah Marzoeki yang sajiannya lebih rileks, tidak menakutkan.
Kehadiran pustaka fisafat, yang demikian itu (santai, populer) adalah tonggak tersendiri. Yang berhasil membumikan fisafat. Keluar dari cangkang “seram” yang mengerutkan dahi membacanya. Alhasil, penjualan bukunya pun terbilang lumayan.
Namun, dibanding genre buku lainnya, buku filsafat tidak sebasah buku umum. Jarang menemukan buku filsafat terjual 3.000 eksemplar/ tahun.
Apakah memang secara filsafat, buku filsafat penting tapi kurang laku?