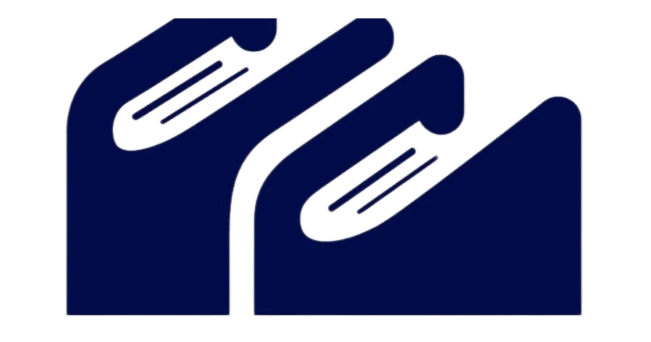Sebelum kompeni Belanda dan kolonial Belanda menancapkan kuku, Biaju sudah memiliki dua gelar, yaitu Orang Dagang dan Man of the Sea (Orang Laut). Jika sebutan sebagai Orang Dagang dari penguasa Daha, maka sebutan sebagai Manusia Laut justru datang dari orang-orang Melayu.
Tetapi, dalam pandangan sebagian orang saat ini, Dayak adalah orang hulu yang tidak mengenal industri dan perdagangan. Kita boleh menuduh, mereka yang masih memegang narasi itu kurang modal yang bernama suntikan literasi. Mereka kurang disuntik pengetahuan sejarah. Tidak heran, dalam benak mereka Dayak adalah ‘manusia pedalaman’. Kita tidak menolak terminology itu seratus persen, cuma ingin menegaskan bahwa Dayak ada di laut, bandar, pesisir sampai pedalaman. Setidaknya diwakili orang Biaju.
Tatkala kita mencermati bait per bait Hikayat Banjar, kita akan bertemu kepada suatu paparan bahwa di Muara Bahan (Marabahan), bandar dagang utama kerajaan Daha ada kelompok pedagang pribumi, yang disebut orang Biaju. Kerajaan Daha itu eksis pada abad ke-14 dan ke-15 (1437-1526 M). Bersama orang Cina, Melayu (Malaka, Damasraya, Johor), Bugis, Makasar, Patani (India), Gujarat (Arab), Palembang, mereka itu (kaum Biaju) dikelompokkan sebagai orang-orang negeri lain yang adatnya pantang ditiru oleh orang-orang Daha. Dalam Hikayat Banjar, hal ini terlihat pada bagian 9, ayat 5, baris 1 sampai 4.
Disebut Negeri Biaju, karena kawasan Biaju memiliki otonomi seperti halnya negeri takhlukan Majapahit, yaitu ; Sukadana, Sambas, Batang Lawai (Sintang, Sanggau), Kutai, Berau, Pasir, Karasikan yang membayar upeti kepada Majapahit, namun disetorkan ke Dipa serta Daha (selanjutnya). Mereka, para pedagang non Biaju adalah pendatang asing yang berdagang dan berdiam di bandar Muara Bahan. Pada zaman pendudukan Kompeni dan Kolonial Belanda, pedagang non pribumi (bukan Banjar dan bukan Biaju) tunduk kepada hukum Belanda.
Ketika di Daha, jelaslah orang-orang Biaju ini belum memeluk agama samawi (Islam dan Kristen). Mereka masih memeluk agama leluhur. Agama samawi hadir di Borneo Selatan saat kerajaan Banjarmasih berdiri dan Daha runtuh, Pangeran Samudera menjadi Islam di hadapan penghulu Demak. Berturut-turut selanjutnya para pemimpin Biaju di muara, seperti Patih Balit, Patih Muhur, Patih Kuin, Patih Balitung juga menjadi Islam. Sebelum menjadi Islam, mereka menjalankan kebiasaan sebagai orang Biaju. Hal itu terlukis dalam Hikayat Banjar bagian 12, ayat 1, bait 25 sampai dengan 52. Di tangan orang Biaju, Raja Bandarmasih yang baru dilantik itu, dibuat mabuk tuak sampai terhuyung-huyung. Mengapa Pangeran Samudera boleh minum tuak dan mabuk? Sebelum menjadi Islam pada 1526, Samudera adalah Dayak Hindu (Schwaner, 1853 : 50), yaitu Dayak yang memegang adat Majapahit.
Biaju yang menjadi pedagang dan menguasai lautan dilukiskan James Cowles Prichard, dokter dan etnolog Inggris yang menjadi admistratur colonial Inggris, dalam bukunya Researches into The Physical History of Mankind volume V, terbit 1847. Dalam narasi Prichard, Biaju adalah suku di pantai Selatan Borneo dan paling maju di Borneo. Kala Prichard menuliskan bukunya, istilah Kalimantan Tengah belum dikenal. Oleh karena itu, orang-orang berbahasa Melayu menyebut Biaju sebagai “Manusia Laut” yang diterjemahkan Prichard sebagai “Man of the sea”. Prichard menyimpulkan nama tadi bukan karena membaca dokumen Belanda. Pedagang Biaju menjual barang-barang ke orang Inggris dan Prichard adalah pegawai kolonial Inggris. Oleh karena itu, Prichard mengetahui perihal Biaju karena Inggris bersentuhan dengan Biaju. Maka tidaklah heran, di bagian lain, Prichard menyebut Biaju sebagai gypsy of the ocean atau gipsy lautan.
Disamping menerbitkan karyanya sendiri tahun 1854, pada tahun 1853 dan tahun 1854 Pijnapple mempublish karya Schwaner yang berjudul Borneo. Karya itu mengupas Tanah Dayak dan Biaju secara lengkap. Schwaner menjelajahi kerajaan Banjar, kerajaan Sintang, Barito, Kahayan, Katingan, Kapuas – Melawi dan menarasikan dalam buku volume I dan II. Pijnapple membahas Katingan, Sampit dan Kotawaringin.
Tidak semua Biaju adalah pedagang. Hanya Biaju Bakumpai yang berpusat di Muara Bahan (Marabahan) dan Biaju Pulau Petak (Kuala Kapuas) yang tercatat memiliki data-data sebagai pedagang. Dari catatan Schwaner kita bisa melihat bahwa kedua kelompok Biaju ini sepertinya sudah membagi wilayah jelajah untuk berdagang. Kelompok Bakumpai menguasai kawasan Barito serta menjelajah sampai ke Mahakam, sedangkan kelompok Pulau Petak menguasai Kahayan, Katingan, Mantaya serta menjelajah sampai ke Malahoi (Melawi).
Para pedagang Biaju ini tidak saja mengambil barang-barang di Bandar, mereka juga membeli barang dari Singapura dan Jawa. Barang dari luar Borneo ini dijual ke kawasan jelajah mereka. Schwaner mencatat para pedagang Biaju ini memasok semua kebutuhan hidup orang Dayak, seperti : tembakau, gambir, garam, batu akik (lamiang), besi, timah, senapan, tembikar, tempayan, guci, kain dan lain sebagainya. Dari kawasan orang Dayak mereka membeli hasil alam (kayu ulin, rotan, damar, madu, dsb), emas, batu geliga sampai sarang burung.
Para pelancong, khususnya Schwaner mencatat hanya pedagang Biaju yang berani masuk ke sungai-sungai yang dihuni orang Dayak. Orang Melayu, Cina dan bangsa-bangsa non pribumi hanya berani berdagang di Bandar. Di Katingan, mereka hanya sampai di Mendawai, di Mantaya hanya sampai di Bandar Sampit. Di Kahayan, pedagang Cina, Banjar serta orang asing dilarang masuk. Pedagang non Biaju tidak berani berdagang ke pedalaman karena takut kena kayau dan perampokan.
Kelompok pengayau menghargai nilai kepala berdasarkan bangsa mereka. Hanya dengan memandang sekilas, orang Dayak paham, bangsa apa pemilik kepala itu. Perelaer mencatat, nilai tertinggi ditempati orang Eropa, nomor dua ditempati orang Cina, nomor tiga orang Banjar dan Melayu, serta yang nomor empat atau terendah adalah orang Dayak. Kepala prajurit Belanda yang dipotong saat Perang Banjar dihargai sekitar 4.000 gulden di Hulu Kahayan.
Biaju Marabahan (Bakumpai) dan Biaju Pulau Petak (Ngaju) ketika Schwaner menjelajah tidak melakukan pengayauan. Bakumpai sudah menjadi Islam sejak kerajaan Banjarmasin berdiri, sedangkan Biaju Pulau Petak, meskipun baru menerima pengaruh Eropa sekitar tahun 1835, kawasan ini sudah lama bersentuhan dengan dunia luar. Meskipun tidak mengayau, kelompok ini paham dengan adat kayau-mengayau. Pemahaman inilah yang membuat mereka berani masuk berdagang ke kawasan yang masih kental dengan tradisi kayau dan perang. Orang Bakumpai memiliki Kuta (pemukiman berbenteng) di Lalutung Toer, apabila ada berita asang (perang besar) yang akan menyerang Barito, maka orang-orang Bakumpai di sepanjang sungai Barito akan masuk ke Kuta (baik manusia maupun dagangannya). Schwaner mencatat, Kuta Lalutung Toer adalah Kuta paling banyak penghuninya di Barito. Orang Pulau Petak tidak masuk ke kawasan Barito dan Mahakam, namun di tempat lainnya mereka tidak dimusuhi suku-suku pengayau.
Tahun 1845 atau sekitar 319 tahun pasca berdirinya kerajaan Banjarmasin, Marabahan hanya terdiri dari 703 rumah, dihuni 5.265 jiwa. Kampung ini sepi untuk ukuran Bandar, karena tidak semua orang Bakumpai tinggal di Marabahan. Orang Bakumpai menyebar ke sepanjang sungai Barito (anak-anak sungai Barito), menyatu dengan orang Pulau Petak di Kuala Kapuas dan sebagian lagi ke Mahakam untuk menjalankan misi perdagangan. Karena berdagang, orang Bakumpai menguasai banyak bahasa. Mereka menguasai bahasa Melayu, bahasa Banjar, bahasa Biaju dan bahasa Dusun. Karena hampir semuanya beraktivitas di dunia dagang, Schwaner tidak menemukan orang Bakumpai meneruskan tradisi leluhurnya dalam hal berladang. Orang Bakumpai benar-benar meninggalkan tradisi berladang karena hampir 100 persen menjadi pedagang.
Tahun 1845, Bakumpai adalah kelompok elit yang mengontrol perekonomian kerajaan Banjarmasih (sebutan awal untuk Banjarmasin). Mereka mengontrol pasokan barang-barang ke Nagara, Barito dan bahkan mengontrol para pedagang Pulau Petak yang memasok barang-barang ke Kahayan. Sebagai kelompok pedagang yang menjual kain, orang Bakumpai sudah mengenal fashion sejak lama. Para perempuan Bakumpai senang menggunakan kain bewarna terang dalam kehidupan sehari-hari. Identitas yang melekat pada Bakumpai adalah Islam dan Biaju.
Kelompok Pulau Petak berada di Ketemanggungan Pulau Petak, sebuah kawasan ketemenggungan yang cukup besar. Tahun 1845, sistem feodalisme masih berlaku di sini (ada kasta bangsawan, kasta budak dan orang merdeka). Saat itu, penduduk Pulau Petak sekitar 14.000 orang. Dari 14.000 orang ini, sekitar 1.000 adalah pedagang. Para pedagang ini kelompok orang merdeka. Mereka menguasai aliran sungai Kapuas Murung, sungai Kahayan, sungai Katingan, Bandar Sampit, sungai Mantaya dan berdagang sampai ke sungai Melawi (Kalbar).
Pijnapple mencatat, pengaruh orang Pulau Petak sangat besar di Sampit. Tahun 1845, Bandar Sampit berpenduduk 3.750 orang. Dari jumlah itu, ada 1.950 adalah orang Dayak, 200 pedagang Melayu dari negeri lain, 1.600 adalah warga setempat yang sudah masuk Islam (Dayak Islam). Pedagang Dayak di Sampit adalah orang-orang Pulau Petak, yang bukan pedagang adalah petani dari Katingan dan Seruyan. Orang-orang Dayak di Sampit menghasilkan Jung yang sangat bagus. Perihal Jung Sampit yang sangat bagus sudah ditulis  oleh Tome Pires, penjalah Portugis yang mendahului orang-orang Belanda dan Inggris. Oleh para pedagang Dayak di Sampit, jung ini dijual ke Jawa dan Singapura (Pijnapple, 1854 : 314). Jung adalah kapal dagang (tongkang) yang bisa berlayar di laut. Jung buatan orang Dayak terkenal kuat dan tahan lama, karena berbahan kayu ulin.
oleh Tome Pires, penjalah Portugis yang mendahului orang-orang Belanda dan Inggris. Oleh para pedagang Dayak di Sampit, jung ini dijual ke Jawa dan Singapura (Pijnapple, 1854 : 314). Jung adalah kapal dagang (tongkang) yang bisa berlayar di laut. Jung buatan orang Dayak terkenal kuat dan tahan lama, karena berbahan kayu ulin.
Jejak orang Biaju di kawasan Batang Lawai (Kapuas) memang tidak tercatat sebagai pedagang. Mereka ada dalam sastra lisan suku-suku yang pernah menetap di Tampun Juah dan Labai Lawai, dianggap penyebab hijrahnya leluhur beberapa sub suku yang saat ini menetap di sepanjang sungai Kapuas. Berangkat dari catatan, Schwaner, kaum Biaju memang sudah melalang-buana melewati sungai Kapuas, dari muara sampai ke Melawi.
Menurut Perelaer, ketika Belanda berkontrak dengan sultan Banjar, perdagangan kaum Dayak menerima imbasnya. Orang-orang Dayak dilarang berlayar ke luar. Ini membuat tradisi berlayar menjadi hilang dan jung-jung kuat itu membusuk. Barulah saat Kolonel Verpick menjadi gubernur militer di Banjar, perdagangan bagi orang Dayak mulai diizinkan tahun 1862. Namun saat itu perang Banjar berkecamuk, tidak mudah bagi kapal dagang untuk hilir-mudik. Akibatnya, profesi yang ditekuni berabad-abad itu hilang begitu saja dari kebudayaan orang Biaju.
Damianus Siyok