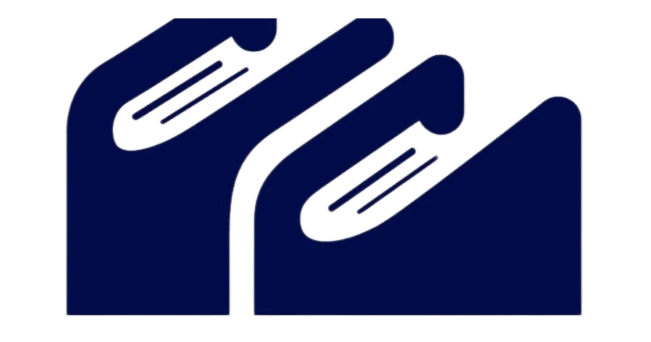Ada peribahasa sarat makna. Dirangkai dalam patah kata Latin yang bunyinya demikian ini. “Ubi societas ibi iustitia est”.
Artinya: di tempat terdapat masyarakat dan adanya kehidupan, maka di sana ada hukum (keadilan).
Itulah manusia Dayak. Penghuni asli bumi Borneo. Yang salah satu, dari multifacet, perikehidupannya dinarasikan dalam buku ini. Buku yang tidak tiba-tiba. Namun, mulai dari awal sekali.
Pada mulanya adalah sepatah kata: ladang.
Mengaji dari alif – demikian adagium yang kerap mampir di gendang telinga kita. Menggambarkan segala sesuatu. Bahwa apa pun itu, senantiasa diawali dari yang pertama.
Demikianlah perjalanan panjang buku ini. Berawal dari satu dua artikel di Web terhormat lagi berkelas ini. Saya kembangkan. Mengajak serta seorang pakar di bidangnya. Untuk mencermati metodologi, memberi afirmasi, sekalian mengoreksi.
Demikianlah. Dari pemikiran kecil artikel, dikembangkan jadi: buku. Begitulah pikiran berkelindan. Bekerja tanpa kata, meski menggunakan kata-kata.
Sekali peristiwa. Sebuah helikopter berputar putar di udara, kemudian menyiram dari atas lahan ladang yang sedang dibakar pemiliknya; ditembaki penduduk. Adegan itu, tak ubahnya film Rambo. Dicari pelakunya. Kemudian, dihukum. Namun, helikopter, awak, dan yang menyuruh; tidak tersentuh.
Peladangan. Bukan “perladangan”. Berbeda sekali maknanya. Periksa saja di KBBI. Itulah topik yang menggelitik kami, sebagai cendikia. Mencoba merentang. Surut jauh ke belakang. Bertemulah dengan para penulis topik sama, sebelum kami, yang berkanjang berkutat menggeluti kajian peladangan suku bangsa Dayak. Namun, tentu beda narasi dan sudut pandang.
Para penjelajah, antropolog, dan penulis Barat (Nieuwenhuis, 1894), Hedda Morrison (1957), Guy Sacerdoti dan Jenkins (1978) menarasikan sistem peladangan manusia Dayak bersahabat dengan alam, tidak merusak lingkungan, dan kultivasinya bukan padi semata-mata, 17 jenis padi, namun juga berbagai macam nilai adat tradisi yang terdapat di dalam seluruh rangkaiannya.
Namun, mengapa? Justru di era milenial, para peladang tradisional Dayak dianggap kriminal, dimejahijaukan di muka pengadilan? Mereka diadili di depan sanak famili sendiri serta disumpah di atas tanah tembuniknya sendiri?
Adakah agenda tersendiri di balik fenomena itu? Misalnya, hasrat untuk semakin memarjinalkan etnis, tradisi, adat serta budaya yang oleh Mochtar Lubis digambarkan bahwa praktik peladangan dengan membakar lahan telah dipraktikkan manusia di muka bumi ini sejak 10.000 s.M.?
Kajian akademik ini menjawabnya!
Ladang, sejak zaman dahulu kala, menjadi tumpuan hidup keluarga Dayak. Nenek moyang kami telah terbukti berladang secara arif bijaksana. Suatu pengetahuan-diam (tacit knowledge) yang patut untuk dikagumi.
Sebenarnya, hingga tahun dekade pertama abad 20, sistem peladangan manusia Dayak tidak ada yang menggugat. Hal itu karena di bumi Kalimantan belum marak perusahaan perkebunan, utamanya perkebunan sawit yang mengeksplotitasi tanah dan hutan secara tidak bijak.
Membakar ladang, ternyata, di luar Jawa dan tanah Sunda yang diwarisi subur dan banyak gunung apinya. Tak ubahnya dengan letusan gunung api. Yang sisa-sisa pembakarannya, sehabis gunung memuntahkan isi perutnya, hanya akan menyuburkan tanah. Jika di Tanah Jawa dan Sunda tidak ada yang menangkapi “pelaku” pembakaran gunung api. Mengapa di Tanah Dayak ditangkapi? Padahal, hasil pembakaran itu sama-sama menyuburkan tanah?
Orang Dayak menggunakan sumberdaya alam secukupnya saja. Bagi mereka, alam adalah “kulkas hidup”. Bahkan, menebang, atau memotong tanaman tertentu tanpa alasan yang kuat, mendapat sanksi adat. Mencemarkan air, dan menuba ikan tanpa memperhatikan lingkungan, kena hukum adat.
Siklus peladangan orang Dayak mengenal musim. Bulan Mei-Juni, biasanya menebas. Awal Juli-Agustus seluruh lahan ladang mengering, siap dibakar pada puncak musim kemarau bulan Agustus. Akhir Agustus hingga awal September, musim hujan. Masa itulah menugal, menanam aneka sayur, temasuk padi dan jagung.
Ketika pada musim kemarau (Agustus-September), pembakaran mengakibatkan asap, maka dituduhkanlah orang Dayak, para peladang tradisional, sebagai pelaku sekaligus penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Padahal, asap akibat peladangan hanya sebentar saja. Dalam tempo tidak lebih dari 4 jam, ladang dan sekitarnya telah bebas dari asap. Hal itu karena ketika membakar ladang, orang Dayak memerhatikan arah angin.
Sudahlah tentu, banyak orang Dayak protes. Sebagian malah merasa dikambinghitamkan. Di Kalbar, di Kabupaten Sanggau dan Sintang, bahkan peladang diajukan ke meja hijau. Untungnya, setelah Sidang, mereka dibebaskan.
Meski demikian, tindak menangkap peladang tradisional Dayak itu sungguh terasa amat menghina. Seakan-akan menyalahkan adat, budaya, dan tradisi yang sejak 10.000 tahun sebeluh Masehi telah dipraktikkan. Harkat dan martabat orang Dayak diinjak-injak. Harga mulia diri mereka, sebagai pewaris tanah dan bumi Borneo, dihinakan.
Menangkap, mengadili, dan memenjarakan peladang Dayak yang mengusahakan lahannya sendiri bagai menangkap tuan yang sedang bekerja di rumahnya. Betapa tragis, sekaligus dramatis peristiwa semacam itu.
Oleh karena orang Dayak merasa “tuan rumah”, sedangkan praktik peladangan telah diwarisi sebagai adat budaya, maka tindakan “menangkap” dan menyalahkan praktik baik (best practice) berladang dianggap telah menghina, sekaligus menista dan menyalahkan adat, budaya, dan nilai tradisi nenek moyang suku bangsa Dayak sebagai suatu kaum.
Di salah satu kecamatan di Sanggau, Kalimantan Barat. Pernah sekali peristiwa. Sebuah helikopter berputar putar di udara, kemudian menyiram dari atas lahan ladang yang sedang dibakar pmiliknya, ditembaki penduduk. Dicari pelakunya. Kemudian, dihukum. Namun, helikokter, awak, dan yang menyuruh; tidak tersentuh.
Di salah satu kecamatan di Sanggau, Kalimantan Barat. Pernah sekali peristiwa. Sebuah helikopter berputar putar di udara, kemudian menyiram dari atas lahan ladang yang sedang dibakar pmiliknya, ditembaki penduduk. Dicari pelakunya. Kemudian, dihukum. Namun, helikokter, awak, dan yang menyuruh; tidak tersentuh.
Ketika studi S-2, mata kuliah Epistemologi. Saya mafhum. Dan tercelik bahwa tidak seorang pun ilmuwan yang tidak berpihak –setidaknya berpihak pada kebenaran. Dan tidak ada penulis yang tidak bias, termasuk media (Cirrino, 1974).
Saya bertanya kepada pemilik ladang yang pernah dirisam helikopter dari atas udara ketika ladangnya sedang dibakar. Kata mereka, “Jahat oooo air itu. Semprotan bukan air biasa. Bikin api segera padam. Dan ranting serta dahan kayu dan bambu lama membusuknya.”
Kearifan lokal, yang diturunkan generasi ke generasi, membuat orang Dayak mahir di dalam membakar ladang, bukan membakar hutan.
Lihatlah! Tak ada api menjalari lahan yang bukan lahan ladang, sebab dibuat marka, atau pembetas, agar api tidak merembet ke luar lahan ladang. Sedangkan abu dan arang dari sisa-sisa pembakaran lahan ladang, akan menjadi pupuk organik.
Dibasahi oleh air hujan, masuk meresap ke dalam tanah menjadi pupuk alami. Sangat mustajab untuk menyuburkan, sekaligus mengharumkan, aneka jenis kultivasi di ladang, seperti: cendawan, sayuran, termasuk padi dan aneka palawija.
Membakar ladang, ternyata, di luar Jawa dan tanah Sunda yang subur dan banyak gunung apinya. Tak ubahnya dengan letusan gunung api. Yang sisa-sisa pembakarannya, sehabis gunung memuntahkan isi perutnya, hanya akan menyuburkan tanah.
Jika di Tanah Jawa dan Sunda tidak ada yang menangkapi “pelaku” pembakaran gunung api. Mengapa di Tanah Dayak ditangkapi? Padahal, hasil pembakaran itu sama-sama menyuburkan tanah?
Oleh pupuk alami itu, nasi dari bulir-bulir padi ladang sungguh perisa, dan enak luar biasa. Organik, murni alami, lagi sehat untuk dikonsumsi. Itu sebabnya, orang kampung sehat-sehat, berusia panjang, melebihi orang kota yang terkontaminasi makanannya oleh pupuk kimia dan pola hidup yang serbainstan.
Sebagai anak peladang, kami mafhum apa yang kami lakukan. Yang tidak paham sistem peladangan, pasti dia: pendatang, atau bukan-penduduk asli. Tapi, seiring dengan tekanan dan tuntutan masyarakat-adat
Kalimantan, bukan hanya Dayak. Pedoman membakar ladang telah pun dibuat. Di Kalbar, Gubernur Sutarmidji –yang nota bene bukan asli Dayak– malah mengeluarkan Peraturan Gubernur. Yang isi peraturan berpihak pada peladang.
Dalam hal ini, bolehlah disematkan predikat kepada Tarmidji sebagai “Gubernur Melayu berhati Dayak.” Sebab, ia mengeluarkan Pergub yang menguntungkan peladang tradisional yang umumnya masyarakat Dayak.
Dan memang, tahun 2020, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Pada bulan Agustus-September tidak ada asap mengepul di bumi Borneo. Padahal, orang Dayak tetap membakar ladang.
Ketika kuliah S-2, mata kuliah Epistemologi. Saya mafhum. Dan tercelik bahwa tidak seorang pun ilmuwan yang tidak berpihak –setidaknya berpihak pada kebenaran. Dan tidak ada penulis yang tidak bias, termasuk media (Cirrino, 1974).
Berpihakkah kami menulis buku ini. Yang dengan gamblang dan terus terang apa adanya memaparkan apa adanya modus vivendi (cara hidup) dan modus essendi (cara berada) manusia Dayak terkait dengan salah satu aspek kehidupannya, yakni: berladang?