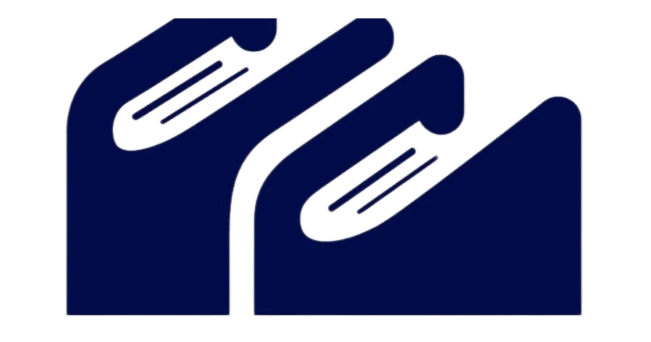Dipikir-pikir sekarang. Lancang juga ya, saya di usia belum lagi 30 tahun. Memberikan Catatan atas buku Catatan Seorang Misionaris yang berkarya selama puluhan tahun di tanah Dayak ini?
Tapi itu telah terjadi. Berlalu sebagai lembar sejarah masa silam. Tanpa terasa, 30 tahun telah lewat.
Buku ini penting. Saya mafhum dari Dr. Yusriadi. Katanya, profesor mereka di Univerity Kebangsaan, Malaysia, Prof. Collins mewajibkan pustaka ini dibaca setiap mahasiswa. Menggambarkan perikehidupan Dayak di masa lampau. Membaca buku ini, mendapat semacam vorurteil.
Tapi yang saya muat di narasi ini adalah Catatan saya pada buku ini. Yang kini sedang disiapkan cetakan edisi terbarunya. Edisi perdana buku ini diterbitkan PT Grasindo, 1992, hlm. xi-xviii.
LUKISAN YANG HIDUP TENTANG “SI KECIL”: MEMAHAMI CATATAN SEORANG MISIONARIS
Oleh: R. Masri Sareb Putra
Semula, buku ini merupakan ”catatan harian” Pater Herman Josef van Hulten. Suatu hasil pengamatannya secara langsung atas semua dimensi dan fenomenologi kehidupan suku Dayak, suku yang selama kurang lebih 30 tahun ia tinggal dan hidup diantara mereka. Sebagaimana halnya survei langsung lapangan, penulis tidak banyak mengutip sumber-sumber luar yang sekiranya dapat membenarkan – atau minimal mendukung-pendapat atas apa yang ditulisnya. Dan menurut saya, justru di sinilah letak kelebihan buku ini: mengungkap suku Dayak secara polos, apa adanya.
Ditinjau dari segi keilmuan pun, yakni ilmu antropologi, pendekatan deskriptif sangatlah bisa dipercaya. Apalagi, Pater Herman hidup di antara suku Dayak. Pengamatannya yang cermat serta alur pemikiran nya yang konvergen dan divergen, terungkap dalam buku ini. Di satu pihak penulis mencoba mengambil jarak, tetapi di pihak lain terkesan bahwa dia sendiri tidak lari dari kehidupan suku Dayak, masyarakat “tersudut” yang sangat dikasihinya.
Tetapi justru karena latar belakang itu, saya amat menaruh respek atas buku ini. Menempatkan hasil pengamatannya atas suku Dayak di dalam buku ini ke dalam alur pemikiran itu, saya justru harus mengangkat topi untuk karya ini. Mengapa harus mengangkat topi? Karena apa yang ditulis Pater Herman, sungguh-sungguh mencerminkan perikehidupan suku Dayak pada saat itu. Dikatakan ”pada saat itu”, karena sekarang tentu saja keadaannya sudah berbeda.
Kejujuran penulis tampak dari sorotannya yang berimbang. Di satu pihak terkadang ia mengkritik suku Dayak seperti adat tradisional mereka yang mengikat, sifat “pemalas”, pemboros, dan suka mencari jalan pintas. Namun, di pihak lain, dia juga memuji suku ini. Di mata Pater Herman, Suku Dayak itu jujur, ramah, bersahabat dan sopan santun. Saya pikir ini adalah lukisan manusia Dayak yang utuh. Itu sebabnya, saya merasa tidak ada judul yang lebih tepat lagi untuk kata pengantar ini kecuali ”Lukisan yang hidup tentang si kecil”, karena memang Pater Herman secara hidup melukiskan suku Dayak, Si Kecil, yang harus diangkat dan menarik perhatiannya.
Kalau mengungkit alasan kedatangannya ke pulau Kalimantan, menjadi jelas bahwa tujuan semula ia menginjakkan kaki di sini pertama-tama bukan untuk meneliti dan menulis buku mengenai suku Dayak. Akan tetapi, tujuannya untuk memberitakan Injil/Khabar Gembira di tengah-tengah suku Dayak.
Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dia sendiri memilih judul untuk buku yang ditulisnya dengan Mijn Leven Met De Daya’s. Sebagaimana diakuinya, dia merasa senasib dan sepenanggungan – bahkan seperasaan dan sehati sejiwa – dengan para Dayak yang amat dikasihinya. Kasih sayang dan rasa persaudaraan itu, terpancar dari sikap-sikap nyata beliau. Pater Harman, misalnya, tidak pernah habis-habisnya memikirkan jalan keluar agar para Dayak-nya tidak kelaparan. Untuk itu, ia mendirikan proyek-proyek sawah percontohan, suatu budidaya padi yang sering dilihatnya di pulau Jawa. Ia juga rajin bertourne, bukan sekadar untuk melihat dari dekat nasib saudar-saudaranya, tetapi lebih-lebih untuk menghayati secara nyata kehidupan para Dayak. Pater Herman memang Dayak sejati. Hanya saja kulitnya yang putih. Namun, hati dan perhatiannya seluruhnya diberikan untuk suku ini.
Meskipun demikian, bukan berarti dia pilih kasih. Bukan, sama sekali bukan! Sebagaimana diakuinya, ia lebih memilih untuk mencintai dan mengangkat yang kecil. Sebab “si kecil”-lah yang selalu memerlukan pertolongan. Dasar pilihannya ini adalah teladan Kristus, Sang Guru, yang sangat dijunjung tinggi olehnya.
Buku ini penting. Saya mafhum dari Dr. Yusriadi. Katanya, profesor mereka di Univerity Kebangsaan, Malaysia, Prof. Collins mewajibkan pustaka ini dibaca setiap mahasiswa. Menggambarkan perikehidupan Dayak di masa lampau.
*
Antropolog dan penulis Barat yang banyak meneliti suku Dayak melakukannya, Orang Dayak adalah penguasa pulau Borneo (Kalimantan) yang tak ada tandingannya. Mereka itu jujur dan ramah tamah. Perawaakannya tampan, sehat, dan berkulit bersih. Laki-laki Dayak berburu dengan senjata sumpit yang panjangnya sampai tujuh kaki, membawa parang yang diukir dengan sangat indah. Mereka memiliki kebudayaan yang sangat tinggi. Mereka memiliki kebudayaan tinggi, berpusat di rumah-rumah panjang (betang) semacam apartemen.
Barangkali, ini gambaran masa lalu, ketika modernisasi belum menjamah pulau Kalimantan. Sekarang, melalui kombinasi dari macam faktor, gambaran diatas berada dalam ambang kepunahan. Dalam banyak hal, ancaman tersebut pantas disesalkan. Itulah yang menyebabkan David Jenkins, wartawan Far Eastern Economic Review usai mengadakan riset di Sanggau Kapuas, Kalbar, pada tahun 1978 menulis: ”Orang Dayak, selamat tinggal semuanya itu!”
Satu dari sekian penyebab hancurnya kebudayaan tradisional Dayak – menurut Jenkins – karena pemerintah RI sejak tahun 1970-an dengan gencar melakukan “pembudayaan” terhadap suku Dayak. Untuk mencapai cita-citanya itu, jalan yang ditempuh, antara lain, dengan menggalakkan program transmigrasi. Sebab, menurut pandangan pemerintah (begitu seperti yang di tulis Jenkins dalam Review Juni 1978) tata cara hidup penduduk asli pulau Kalimantan yang berjumlah 2-3 juta jiwa itu, bisa merusak image bangsa Indonesia di mata luar negeri sebagai sebuah negara yang progresif.
Pernyataan itu sangat ironis. Sebab, sejarah mencatat, pulau Borneo pernah amat mencengangkan dunia. Sekitar abad 17, Borneo dikenal sebagai kawasan yang makmur di seluruh Hindia Belanda karena hasil karet dan kopranya. Sehingga muncul satu istilah pada waktu itu yang dengan tepat melukiskan kemakmuran Borneo dengan sebutan ”Zaman Kupon”.
***
Kata “Dayak” berarti orang udik, yang tinggal di pedalaman. Perbedaan penulisan nama suku tersebut, walaupun hanya satu huruf tambahan (huruf “k”), bagi suku Dayak sangat berarti. Menjadi lebih bermakna, apabila diingat bahwa dengan mengucapkan “Dayak” maka suku Dayak akan merasa terhina.
Jika kita memiliki pengetahuan mengenai tata bahasa Belanda, kita segera akan tahu bahwa penulisan yang benar adalah Daya (tanpa “k”). Sebab bahasa Belanda selalu menyisipkan konsonan di antara dua huruf vokal untuk membentuk kata benda. Misalnya Java → Javanese, Sunda → Sundanees, Bali → Balinees, dan Daya → Dayaker. Dalam literasi-literasi Belanda, Dayaker tidak pernah digunakan. Yang digunakan ialah “Dayak”, yang disejajarkan dengan kata binnenlander yang berarti: orang/ suku yang bertempat tinggal di pedalaman/orang hulu/ Orang Dayak. Penting diberikan catatan, bahkan di kalangan intelektual Dayak sendiri pun, hingga saat ini belum ada kesepakatan atau keseragaman penulisan (dan pengucapan) mengenai suku “asli” Kalimantan tersebut. Dalam literasi sering kali dijumpai berbagai macam versi, misalnya Dayak, Dyak, Daya’, Daya.
Dalam buku ini, saya kurang berminat memasalahkan manakah yang benar dari empat versi itu. Alasannya sederhana: yang penting maknanya, konsisten menggunakannya, jangan dicampuradukkan, serta bisa menjelaskan alasan mengapa menggunakannya. Saya berpikir, tidak banyak gunanya memasalahkan perbedaan penulisan, hanya akan membuang-buang tenaga saja.
Perihal suku Dayak sendiri, sesungguhnya masih terbagi dalam sub-sub suku. Menurut Dr. H.J. Malincrotd, mantan kontroleur di masa kolonial, suku Dayak dibagi dalam enam rumpun, yang disebutnya dengan stammenras. Enam stammenras itu: (1) Kenya–Kenyan-Bahau, (2) Ot Danum, (3) Iban, (4) Moeroet, (5) Klemantan, dan (6) Poenan. Yang banyak di – soroti dalam buku ini adalah stammentras Klemantan. Sub-suku Dayak sebanyak 405, sementara 147 sub-suku tersebar di Kalimantan Barat.
Jika saja isolasi Kalimantan tidak dibuka, masih banyak orang yang percaya bahwa orang Dayak “suka makan manusia”. Atau malah pemenggal kepala orang (pengayau). Ini sesungguhnya merupakan gambaran salah tentang suku Dayak, suatu politik devide et impera yang disulut Pemerintah Hindia Belanda guna memecah belah bangsa kita. Di samping isu politis, juga merupakan upaya Belanda untuk eksis di nusantara. Sebab karuan saja, gambaran salah itu lalu mempengaruhi citra yang sampai hari ini masih melekat dengan kuat di benak suku-suku lain di Indonesia.
Meskipun jauh sebelum kemerdekaan Indonesia para misionaris Kristen Barat sudah berusaha membuka isolasi di Borneo dengan mendirikan sekolah-sekolah dan rumah sakit di tengah-tengah suku Dayak (seperti di Sejiram, Nyarumkop, dan Benua Martinus), akan tetapi jeratan isolasi yang sangat berarti dibuka awal tahun 1970-an. Untuk mewujudkan semangat pembaruan itu, para pejabat dari pulau Jawa memanfaatkan semua kekuasaan mereka dengan moto “Mengangkat orang Dayak ke atas”, sehingga sikap dan pandangan mereka sesuai dengan norma-norma yang dapat diterima di republik ini.
Di satu pihak usaha yang dilakukan para pejabat itu memang pantas untuk dihargai. Misalnya pemerintah telah membangun jalan-jalan raya – kini malah jalan internasional Pontianak-Tebedu (Malaysia) – dan penyempurnaan lalu lintas perairan sungai. Di samping itu, dibangun pula rumah sakit dan puskesmas yang letaknya masuk jauh ke daerah pedalaman. Diakui, pembangunan itu dengan sendirinya membuat orang Dayak lebih maju dari sebelumnya.
Namun, di sisi yang lain, ada akibat yang juga tak boleh dianggap sepele. Misalnya, pemerintah juga melaksanakan kebijakan yang kurang berkenan dihati penduduk setempat. Beberapa pelaksanaan kebijakan itu bukan saja menyinggung perasaan suku Dayak, melainkan juga bisa mempercepat proses kehilangan identitas mereka. Angkatlah sebagai contoh, kebijakan pemerintah untuk bongkar rumah panjang.
Dibongkarnya rumah panjang, tidak hanya menyinggung perasaan orang Dayak. Selama berabad-abad, membangun kebudayaan mereka di rumah panjang. Terutama di Lawang, yaitu semacam apartemen milik perseorangan diatas tiang-tiang tinggi yang dihubungkan dengan soa (sebuah gang yang luas di dalam rumah). Biasanya, sebuah betang terdiri dari 100 lawang yang panjangnya lebih dari 100 meter. Betang ini bisa berfungsi memberikan perlindungan keamanan secara fisik. Lagipula, dapat menjalin rasa kesatuan.
Soa, yang berlantai bambu, memiliki arti tersendiri. Ia tak sekadar sebuah jalan di dalam rumah. Tapi juga bisa berfungsi ganda sebagai tempat menenun, menerima tamu, tempat para lelaki Dayak mengobrol sambil minum-minum tuak. Soa pun menjadi tempat dilangsungkannya upacara-upacara ritual dan perarakan tradisional. Singkat kata, soa menjadi jantung kehidupan sehari-hari komunitas Dayak.
Saat ini rumah betang sangat langka. Jumlahnya dapat dihitung dengan jari. Para pejabat di Kalimantan mendesak orang Dayak supaya membangun rumah dari kayu secara terpisah. Alasan yang dikemukakan pun bermacam-macam, seperti: kehidupan komunal sebagaimana yang dipraktekkan suku Dayak menyerupai komunisme. Hal ini, menurut pengamatan para misionaris Kristen yang mengenal baik suku Dayak disebut absurd. “Saya tak mengerti bagaimana orang Dayak disebut begitu,” kata Haas, seorang misionaris Barat yang bekerja di kalangan Dayak Kalbar seperti ditulis Jenkins.
Tidak melesatlah apa yang seperti ditulis Jenkins. Bahkan, para pemimpin Dayak yang menjadi pejabat Dayak dengan keras membantah bahwa orang Dayak bisa lebih cenderung jadi komunis. “Di tahun 1967, misalnya, orang Dayak memainkan peranan di dalam pembahasan komunis di Kalbar”, bantah mantan Gubernur Kalbar yang berasal dari suku Dayak, J.C. Oevang Oeray, dalam wawancaranya dengan Review.” Orang Dayak memang suka hidup berkomunal, namun mereka bukan komunis!”
Rumah panjang juga disebut-sebut mengandung bahaya bagi kesehatan dan kebakaran. Sebaliknya, para pemimpin Dayak mengatakan bahwa rumah panjang tidak mudah mengalami kebakaran, kecuali jika disulut orang dengan api. Menurut penuturan para saksi, rumah panjang dibakar oknum pejabat disebabkan orang Dayak tidak mengindahkan perintah untuk membongkarnya.
Alasan lain, yang dikemukakan oleh para oknum pejabat untuk membongkar rumah panjang, ialah karena hidup bersama dibawah satu atap dapat memberikan peluang bagi praktik perilaku seksual secara bebas dan hilangnya standar moral. Bahkan rumah panjang dapat menimbulkan praktek seks berkelompok. Padahal, praktek seks bebas tak pernah ada dalam kehidupan suku Dayak. Tak pernah seorang laki-laki Dayak boleh tidur dengan istri orang lain. Adat mengharuskan, tak seorang pun boleh melakukan hubungan seks di luar status perkawinan yang sah.
Upaya untuk mempertahankan betang, tampaknya menjadi suatu yang sia-sia. Toh begitu, kampanye anti betang telah membuahkan hasil. Kini, misalnya, tak banyak lagi rumah panjang di Kalimantan yang dipelihara dengan baik. Di Sanggau Kapuas, sebuah kabupaten paling utara provinsi Kalbar, sekarang tinggal 8 buah betang saja.
Di beberapa tempat, betang memang masih berdiri. Tapi setidaknya inilah realita dari serangkaian kampanye anti rumah panjang. Seiring dengan itu, tari-tarian tradisional dan hasil kerajinan tangan suku Dayak pun sedang lenyap. Di mana-mana, orang Dayak (di Kalimantan Indonesia) dalam kehidupan sehari-hari tak lagi menunjukkan tarian tradisional. Kecuali jika saat menerima tamu agung atau Tahun Baru Dayak (Naik Dango).
Sebaliknya di Serawak, Malaysia. Tarian, kesenian dan kebudayaan Dayak malah digalakkan secara aktif oleh pemerintah. Dayak di Malaysia masih memiliki rasa bangga akan budaya tradisional mereka.
Hal lain yang menjadi korban modernisasi adalah bahasa. Banyak penduduk Dayak (terutama generasi baru) tidak tahu lagi bahasa ibunya. Hal ini, antara lain, disebabkan karena Bahasa Indonesia diajarkan di sekolah-sekolah.
Orang Dayak di Kalimantan Indonesia pun kehilangan keterampilan sebagai pandai besi. Padahal, dulu orang Dayak amat dikenal karena mandau-nya yang indah, sebuah karya seni yang dipadukan dengan nilai kebudayaan. Dewasa ini, memang masih banyak orang Dayak yang membuat parang. Namun, ukiran khasnya sudah tidak ada lagi. Bahkan, di banyak tempat, orang Dayak lebih suka menggunakan parang buatan Jepang atau Taiwan.
Bukan pesimis, namun bukan tidak mungkin, kalau tidak diwaspadai maka dalam waktu dekat orang Dayak akan kehilangan identitas. Dan segera menyusul pertanyaan: Bagaimana masa depan mereka?
***
Sudah selayaknyalah, pada akhir pengantar ini saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak, yang telah secara langsung dan tidak langsung memberikan bantuan dan dorongan dari awal hingga selesainya karya ini.
Pertama-tama, terima kasih saya sampaikan kepada Bpk. Soedirdja di Madiun, yang menerjemahkan teks asli bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia. Terima kasih yang sama saya sampaikan kepada P. Herman Ahie OFM. Cap., pastoran Tebet yang bersedia memberikan fasilitas berupa komputer untuk mengerjakan buku ini.
Jakarta, Oktober 1992