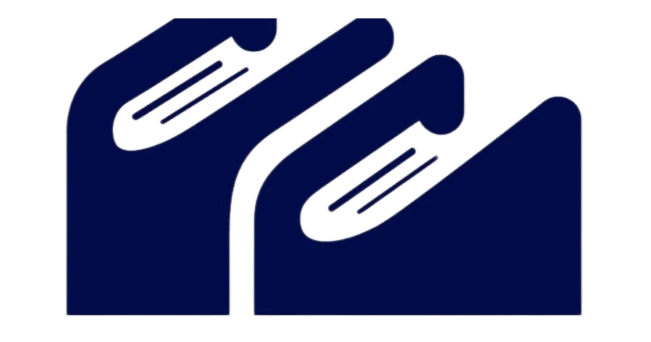Historia vero testis temporum –demikian Cicero (106-43 sM) berkata. Ya, seperti novel fenomenal ini. Ia adalah saksi zamannya. Usai menerima buku ini dari sahabat yang penerbit, Parakitri Tahi Simbolon, saya membacanya. Kemudian, mengulasnya. Dan dimuat koran sore, salah satu papan atas saat itu, yang berkantor di Cawang, Jakarta Timur.
Suara Pembaruan, Rabu, 27 Mei 1998
Judul : Saman
Pengarang : Ayu Utami
Penerbit : Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 1998
Tepal : 197 halaman
Harga : Rp. 18.000
DAHSYAT!
Agaknya, tak ada kata yang tepat untuk melukiskan, betapa novel Saman menjadi buah bibir hari-hari terakhir. Yang membicarakan pemenang Sayembara Roman Dewan Kesenian Jakarta 1998 itu bukan saja para sastrawan dan budayawan, melainkan juga intelektual, cendekiawan, dan kaum religius.
Pasalnya, Saman bukan sekedar karya sastra. Ia adalah karya yang melampaui sastra, sehingga bisa dilihat juga sebagai produk budaya dan pengalaman religius penulis ketika bertemu dan berinteraksi dengan manusia lain, alam, dan Tuhan.
Membaca karya ini dari halaman muka, rasanya tidak ingin berhenti hingga halaman terakhir. Di samping bahasanya yang indah, juga jalinan kisahnya menawan. Ayu berhasil menampilkan daya pikat luar biasa. Seakan-akan ia menyihir pembaca, sehingga begitu memegang bukunya, orang tidak akan berpikir dan berbuat hal lain.
Penulis pun pandai membikin tegang pembaca. Dengan variasi kalimat panjang-pendek, ia berhasil menyuguhkan hidangan memuaskan dan tidak membosankan. Sejak mula halaman depan, kita terpikat, oleh tuturnya bercerita, sehingga tak ingin berhenti hingga halaman terakhir.
“Terik. Angin kencang, datang dari laut dan baling-baling. Seorang lelaki muncul dari tubir pangkalan; ada sebuah tangga di sana, seperti timbul dari tengah-tengah air”. (hlm. 7).
Penggambarannya pada alam sekitar dan situasi begitu hidup, membuat pembaca seakan merasakan sendiri sebagai subjek. Sedemikian rupa, sehingga tak jarang penggambaran itu jadi mencekam. Karena polos mengatakan sesuatu apa adanya, tak jarang kita merasa malu, sebab membaca novel ini kita seolah melihat di cermin diri kita sendiri: Inilah rupaku, aku memang jelek dan berdosa.
Penggambaran seperti itu, menurut Ayu, justru menunjukkan manusia sesungguhnya, yakni manusia yang tak sempurna dan tak luput dari dosa asal.
Di bagian prolog. Ayu mengaku banyak pihak membantunya menulis novel ini. Tiga sosok dengan gamblang disebutnya: Goenawan Mohamad, Tony Prabowo, Prasetyohadi. Kadung, publik seakan menuduh Saman dibuat GM – ditilik dari gaya, dan diksinya, yang khas penulis Caping Tempo itu. Saya malah menyangka: jangan-jangan ini teknik marketing, membuat orang penasaran ingin membuktikan. Lalu membeli. Nyatanya, kini Saman cetak ulang lebih dari 40 kali!
Di bagian prolog. Ayu mengaaku banyak pihak membantunya menulis novel ini. Tiga sosok dengan gamblang di sebutnya: Goenawan Mohamad, Tony Prabowo, Prasetyohadi. Kadung, publik seakan menuduh Saman dibuat GM – ditilik dari gaya, dan diksinya, yang khas penulis Caping Temp itu.
Demikian kita temukan dalam empat sekawan, semuanya perempuan eks SMA Tarkit (Tarakanita), tokoh-tokoh utama dalam novel ini selain tentu saja pastor Athanasius Wisanggeni yang kelak setelah peristiwa “Perabumulih” ganti nama jadi Saman.
Pembalikan Nilai
Apa yang istimewa dari novel ini, sehingga pantas tampil sebagai pemenang lomba penulisan roman DKJ 1998?
Hal yang istimewa adalah: semuanya. Komposisi cerita, bahasa, paradoks, metafora, maupun imaginasi semuanya luar biasa. Setelah sampai pada halaman terakhir, semua setuju bahwa karya ini fenomenal, dan karena itu, menandai lahirnya sebuah angkatan baru sastra Indonesia: Angkatan 90-an.
Sekurang-kurangnya tiga nilai dasar dalam novel ini dibalik Ayu, atau minimal diangkat ke permukaan sehingga semua tampak telanjang apa adanya.
Pertama, dimensi politik. Hal ini tampak pada penggambarannya yang mencekam pada pemberontakan para petani karet Lubukrantau yang diotaki Romo Wisanggeni. Kita melihat di sana, betapa liciknya penguasa pengeksploitasi rakyat kecil. Dibongkar pula di sana jargon-jargon yang digunakan penguasa untuk tetap mempertahankan status quo.
Kedua, sisi religius novel ini tidak datar. Bahkan, dapat dikatakan membongkar bungkus iman Kristen diimani habis-habisan, untuk dilihat kebenaran isinya. Karena Ayu terlahir dari keluarga taat menjalankan ritus Katolik, sangat kental nuansa Kekatolikan (dan Kekristenan) dalam novel ini.
Pengaramh rupanya sangat paham nats Perjanjian Lama, seperti tersimpul di bagian akhir novel ini, dalam surat-menyurat antara Yasmin dan Saman.
Demkian pula di runut cerita mengenai kedahsyatan pengaruh jin dan peri di Perabumulih, agaknya tak lain yang mengilhami Ayu Utami melihat alam gaib dan masa depan kecuali ia bertumpu dan berbekalkan Kitab Wahyu. Penjungkirbalikan nilai religius juga tampak, ketika pastor Wisanggeni mulai merasa Tuhan meninggalkannya, padahal ia berkarya di tengah-tengah umat milik-Nya sendiri.
Ketiga, problema seks merupakan dimensi manarik lain yang disuguhkan penulis. Blak-blakan ia melukiskannya. Ia berani memasuki wilayah yang tak mungkin dijelaskan secara moral, ketika melukiskan deviasi seks sebagaimana dialami Yasmin. “Aku terkena aloerotisme. Bersetubuh dengan Lukas tetapi membayangkan kamu” (hal 195).
Setelah mengikuti sebuah wawancara dengan koran ibukota kita baru mengerti, mengapa penulis melihat seks sebagai suatu hal yang perlu untuk diurai. “Karena memang seks itu menjadi problema bagi perempuan ketimbang bagi lelaki,” ujar Ayu.
Lalu, ibarat kata pepatah tak ada gading yang tak retak, kalau mau dicari titik lemahnya, novel ini pun ada retaknya. Misalnya, ia bilang bahwa bunga bangkai (Rafflesia arnoldi) tumbuh di hutan tropis dataran tinggi Malaya – ini sesuatu yang agak aneh. Atau tanaman karet enam tahun baru bisa disadap, padahal kalau karet unggul (HTI) usia lima tahun sudah bisa diambil latex-nya.
Itu hanyalah kesalahan kecil. Sama sekali bukan setitik nila pada belanga, sehingga bisa merusak semuanya. Yang jelas, itu merupakan kekhilafan kecil yang masih diperbaiki, dan merupakan bagian dari proses kreatif dan semacam tren baru di dalam menulis novel. Kalau ingin berhasil dan detail adakanlah riset.
Di bagian prolog. Ayu mengatakan, banyak pihak membantunya menulis novel ini. Tiga sosok dengan gamblang disebutnya: Goenawan Mohamad, Tony Prabowo, Prasetyohadi.
Meski demikian, tak bisa disimpulkan Saman lalu karya kolektif. Tidak! Sebab, orisinalitas sebuah karya sastra bukan diukur dan kesempurnaan bahasa dan ejaan saja, tetapi – yang sangat dominan – adalah orisinalitas ide dan imaginasi Ayu Utami, tak mungkin orang lain. Karena hanya penulis seusia dialah (29 tahun) bisa begitu!