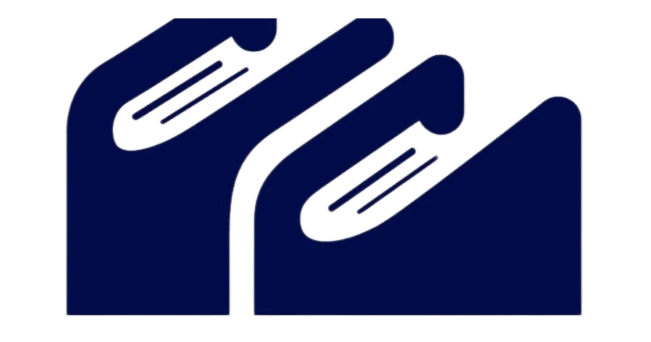Saya adalah imam diosesan Keuskupan Sintang. Ditahbiskan menjadi imam pada tanggal 7 Agustus 2014 di Paroki Maria Ratu Semesta Alam, Sungai Durian oleh Yang Mulia Mgr. Agustinus Agus.
Lewat perkenalan singkat ini, saya hanya mau mengatakan kalau Mgr. Agus mempunyai peran yang sangat penting dalam perjalanan panggilan saya menjadi seorang imam. Oleh karena itu, tulisan ini mohon jangan dilihat sebagai bentuk ketidaksopanan atau rasa tidak hormat terhadap Beliau yang sudah banyak berjasa dalam hidup saya.
Lantas, dalam konteks apa tulisan ini mesti dibaca dan ditempatkan? Dalam konteks berteologi kontekstual di tengah suku Dayak. Tidak lebih dari itu.
Ada banyak tema yang bisa dikaji dan direfleksikan ketika berbicara tentang upaya berteologi kontekstual di tengah suku Dayak. Apalagi bila kita melihat kenyataan di mana gerak hidup manusia Dayak itu hampir selalu diwarnai oleh ritual dan upacara adat. Kenyataan ini dapat menjadi pengingat bagi Gereja, bahwa dalam usaha membangun Kerajaan Allah di tanah Kalimantan, dialog yang jujur dan sabar dengan kebudayaan lokal kiranya menjadi hal sangat penting.
Tulisan ini sendiri akan memokuskan diri pada gagasan dari Mgr. Agus yang melaluinya beliau berupaya menghadirkan dan menghidupkan simbol-simbol budaya lokal dalam karya dan misi penggembalaannya. Sebagaimana dilansir dari majalahduta.com, Mgr. Agus berencana mendirikan sebuah patung raksasa Yesus Kristus di Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang. Dan beliau sudah menetapkan bahwa nama untuk patung itu nanti ialah “Patung Yesus Panglima Burung”.
Sebuah upaya berteologi kontekstual
Lewat gagasan pendirian patung Yesus Panglima Burung, pun juga dari beberapa buah karya yang sudah bisa kita lihat dan nikmati (Rumah Retret St. Yohanes Paulus II, Anjongan, misalnya), Mgr. Agus, yang adalah putra asli suku Dayak, mau menunjukkan kepada kita bagaimana agar budaya lokal jangan sampai dihilangkan oleh Gereja dalam menjalankan tugas pewartaan dan perutusannya.
Upaya beliau tersebut tentu saja bukan tanpa dasar. Dalam hal ini Mgr. Agus mendasarkan dirinya pada sikap dan pandangan Gereja sendiri yang meyakini bahwa Warta Gembira tentang Kristus dan kebudayaan manusia itu mempunyai hubungan yang sangat erat.
Sebagaimana ditandaskan oleh Konsili Vatikan II, dalam dokumen Konstitusi Pastoral tentang Gereja di Dunia Dewasa ini (Gaudium et Spes): “Sebab, Allah yang mewahyukan diri-Nya sepenuhnya dalam Putra-Nya yang menjelma, telah bersabda menurut kebudayaan yang khas bagi pelbagai zaman.
Aneka ragam budaya manusia sungguh dapat menjadi medan pewartaan Gereja menyebarluaskan dan menguraikan pewartaan tentang Kristus, untuk menggali dan semakin menyelaminya, serta untuk mengungkapkannya secara lebih baik dalam perayaan liturgi dan dalam kehidupan jemaat beriman yang beraneka ragam” (Gaudium et Spes, 58).
Bila Gereja sungguh meyakini bahwa aneka ragam budaya manusia sungguh dapat menjadi medan pewartaan Gereja, maka tradisi dan budaya yang menjadi milik manusia Dayak tentu jugalah termasuk di dalamnya. Hal inilah yang kiranya meneguhkan keyakinan Mgr. Agus.
Karena itulah, saat menyumbangkan pemikiran dalam rangka pembukaan program Doktor Teologi di STFT Widya Sasana, Malang, beliau berpendapat: “Masyarakat adalah konteks Gereja setempat berada dan bertumbuh. Gereja tidaklah mengawang-awang; Gereja itu hadir di tengah konteks di mana ia berada dan berkembang. Itulah masyarakat. Maka, masyarakat Indonesia yang khas dengan persoalan dan budayanya harus menjadi locus theologicus” (Robert Pius Manik et al., 2020, hlm. 170).
Kalimat terakhir di atas mau menunjukkan kalau Mgr. Agus sedang menjalankan sebuah teologi yang kontekstual. Dengan teologi yang kontekstual hendak memaksudkan bahwa Injil itu direfleksikan dalam konteks budaya lokal.
Dalam bahasa Rm. Armada Riyanto, berteologi berarti mengakarkan Sabda atau membuat benih itu berakar dalam dan kokoh di kebudayaan manusia sedemikian rupa, sehingga Sabda bukan hanya akan tumbuh dan berbuah, melainkan juga menginjili nilai-nilai kebudayaan hidup sehari-hari manusia (Robert Pius Manik et al., 2020, hlm. x).
Dalam berteologi kontekstual, Mgr. Agus merupakan satu dari sekian banyak uskup (teolog) yang menjalankannya. Di beberapa tempat lain kita bisa menemukan upaya serupa. Misalnya, teologi Dalit (India), telogi Minjung (Korea Selatan), teologi feminist, teologi pembebasan (Amerika Latin).
Sebuah teologi yang kontekstual tidak dijalankan tanpa model dan tujuan. Berkaitan dengan model, jika boleh saya tafsirkan, Mgr. Agus menerapkan model pendekatan antropologi sebagaimana yang digagas oleh Stephen B. Bevans (lihat Gereja Keuskupan Sintang Menghormati dan Menghargai Kebudayaan Lokal).
Dua hal kiranya dapat diangkat dari gagasan yang dikemukakan oleh Bevans di atas terkait dengan upaya berteologi kontekstual yang dijalankan oleh Mgr. Agus. Pertama, Mgr. Agus memandang bahwa kodrat manusia dan konteks kehidupannya adalah baik, kudus dan bernilai. Kedua, Mgr. Agus berusaha mencari pewahyuan dan penyataan diri Allah yang tersembunyi dalam keprihatinan-keprihatinan dari sebuah konteks. Dalam hal ini yang menjadi konteksnya ialah masyarakat Dayak.
Sedangkan persoalan atau keprihatinan yang menjadi locus theologicus-nya ialah kebodohan dan ketertinggalan. Oleh karena itulah, didirikannya patung ini beliau jadikan sebagai simbol pembebasan orang Dayak dari kebodohan dan ketertinggalan baik dari segi pendidikan maupun ekonomi.
Yesus Panglima Burung: Sebuah bentuk inkulturasi
Bagi saya pribadi, nama yang dipilih oleh Mgr. Agus ini menarik untuk dijadikan bahan refleksi, kajian dan diskusi. Menarik, karena sejauh pengetahuan saya inilah pertama kalinya tokoh atau sosok terkenal dari masyarakat Dayak namanya disandingkan dengan nama Yesus. Pemilihan dan pemberian nama tersebut tentu saja bukan tanpa dasar dan tujuan.
Saya sungguh meyakini bahwa nama itu lahir dari buah pembacaan dan refleksi Mgr. Agus atas keadaan manusia Dayak, yang dalam beberapa segi masih mengalami ketertinggalan. Dari beberapa segi itu, Mgr. Agus lebih menyoroti segi pendidikan dan ekonomi. Karena itulah, patung Yesus Panglima Burung ini nanti akan menjadi simbol pembebasan orang Dayak dari kebodohan dan ketertinggalan.
Lewat pilihan nama tersebut, Mgr. Agus tentu mengharapkan agar semangat perjuangan yang dimiliki oleh Panglima Burung, Panglima Suku Dayak, juga menjadi semangat putra-putri Dayak dan siapa saja yang berkehendak baik dalam berjuang untuk membebaskan orang Dayak dari kebodohan dan ketertinggalan.
Harus kita akui betapa Mgr. Agus melalui gagasannya ini menunjukkan perhatian dan kepedulian yang mendalam terhadap kemajuan manusia Dayak. Beliau ingin menggugah siapa saja yang berkehendak baik untuk turut berpartisipasi dalam membebaskan orang Dayak dari kebodohan dan ketertinggalan. Dan dari pihak Gereja sendiri, Mgr. Agus sangat mengharapkan agar Gereja tidak menutup mata terhadap persoalan-persoalan faktual yang dihadapi oleh umat.
Poin terakhir di atas mau menegaskan bahwa bagi Mgr. Agus inkulturasi itu bukan hanya mencakup bidang liturgi saja. Dengan kata lain, inkulturasi tidak sekadar mencakup perayaan misa yang meriah, di mana unsur-unsur dari budaya lokal dimasukkan dalam tata perayaan Ekaristi.
Inkulturasi, bagi Mgr. Agus kiranya senada dengan apa yang disampaikan Rm. Emanuel Marthasudjita, yakni mesti mencakup hal yang lebih mendalam, yakni mengubah kehidupan yang sesuai nilai Injil.
Inkulturasi sebaiknya dipahami sebagai suatu proses yang terus-menerus, dalam mana Injil diungkapkan ke dalam suatu situasi sosio-politis dan religius-kultural dan sekaligus Injil itu menjadi daya dan kekuatan yang mengubah atau mentransformasikan situasi tersebut dan kehidupan orang-orang setempat (Robert Pius Manik et al., 2020, hlm. 174-177).
Dan juga senada dengan apa yang pernah disampaikan oleh Rm. Gregorius Budi Subanar. Dalam kesempatan Seminar Nasional dan Festival Borneo di Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, 8 – 13 Agustus 2018, berkaitan dengan inkulturasi Gereja Katolik di dalam kebudayaan suku Dayak, beliau mengatakan:
“Selama ini, inkulturasi Gereja Katolik ke dalam budaya lokal, termasuk dalam Kebudayaan suku Dayak, masih dilihat sebatas dalam pesta budaya maupun atraksi budaya setiap kali ritual selepas panen padi yang disebut gawai di Provinsi Kalimantan Barat, dan Isen Mulang di Provinsi Kalimantan Tengah, dan lain-lain”
Menurutnya, inkulturasi Gereja Katolik di dalam kebudayaan suku Dayak, mesti dilihat sampai sejauh mana pergulatan Gereja Katolik di dalam menuntun proses kehidupan nyata masyarakat suku Dayak, termasuk di antaranya menuntun hak hidup yang menyertainya berupa hak kepemilikan terhadap tanah, termasuk di antaranya memperjuangkan pengakuan terhadap kepemilikan tanah adat suku Dayak.
Oleh karena itu, Gereja Katolik di Kalimantan mesti mencari formula yang relevan di dalam menuntun masyarakat suku Dayak dalam memperjuangkan haknya atas tanah, terutama tanah Adat Dayak. Karena tanah bagi masyarakat suku Dayak merupakan hak hidup paling mendasar yang menyertainya di dalam kehidupan nyata di tengah-tengah pergulatan global di bidang budaya, sosial, ekonomi dan politik” (independensi.com).
Sumber foto: Majalahduta.com