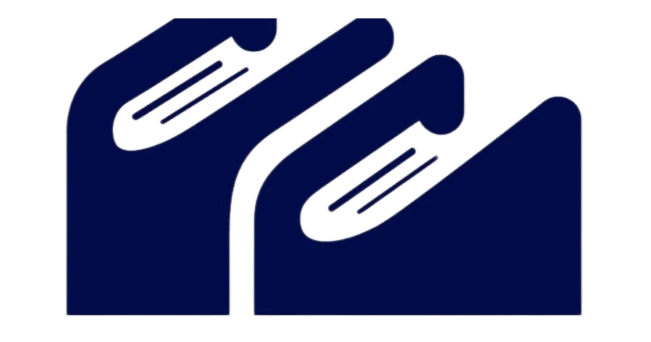Di tengah International Series Book Number (ISBN) kian sulit syarat administrasi dan memakan biaya pracetak, ada saja kreativitas yang muncul.
Kini Google Books menyediakan: Google-Id. Untuk buku yang bukan dijadikan kenaikan pangkat dan golongan, khususnya bagi guru dan dosen, maka ISBN tak diperlukan lagi.
Hari gini, di era digital, siapa pun bisa menjadi penerbit. Hal ini sudah dinujumkan McLuhan puluhan tahun silam.
“Gutenberg made everybody a reader. Xerox makes everybody a publisher.”
Ya, di era digital, di mana kemudahan didapat dari teknologi percetakan (Xerox –dalam bahasa McLuhan), setiap orang mungkin menjadi penerbit. Asalkan, kreatif dan bisa mengolah naskah menjadi buku yang laku dijual.
Selama ini, orang mafhum perbukuan Nusantara awal mulanya menggeliat di ranah Minang. Betapa tidak! Dibanding wilayah lain, di Nusantara, daerah yang banyak melahirkan munsyi dan sastrawan ini lebih dulu eksis. Jauh sebelum Indonesia merdeka, telah ada Penerbit Limbago Minangkabau, Drukkerij Merapi (Bukittinggi), dan Almoenir (Padang). Baru tahun 1917, mendapat saingan dari Batavia dengan tampilnya Balai Pustaka.
Kini mencetak buku 5, bahkan 1 eksemplar, pun dimungkinkan dengan sistem print on demand (POD). Orang tidak bicara lagi soal omset, melainkan net profit dan kecepatan serta efisiensi.
Kemudian baru muncul penerbit besar seperti Djambatan dengan oplah besar. Sarinah, karya Soekarno (1951) dicetak 50.000 eksemplar. Antara 1949-1956, Djambatan adalah market leader perbukuan Tanah Air yang meraup pangsa pasar sebesar 50%.
Tahun 1953, Masagung (Tjio Wie Tay) dan rekannya Adisuria (The Kie Hoat) mendirikan N.V. Gunung Agung. Memasuki dekade 1970-an, PT Gramedia merajalela hingga 1980-1990-an bersama penerbit besar lain, seperti Erlangga, Mizan, Intan Pariwara, Penebar Swadaya, dan lain-lain. Mereka meraja lela hingga tibanya era digital.
Kini menerbitkan buku bisa siapa saja. Pasar lebih tersegmentasi. Oplah tidak lagi harus bicara minimal cetak 3.000 eksemplar. Mencetak 5, bahkan 1 eksemplar, pun dimungkinkan dengan sistem print on demand (POD). Orang tidak bicara lagi soal omset, melainkan net profit dan kecepatan serta efisiensi.
Sewa gudang sudah tidak ada lagi. Demikian pula, biaya membangun dan sewa toko buku tidak ada. Gerai buka 24 jam, setiap waktu, bukan hanya 12 jam per hari. Toko daring menjadi pilihan penerbit era digital.
Seiring itu, penerbit Indie (bebas) dan penerbit daerah kian menggeliat. Seperti kembali ke masa silam, era prakemedekaan. Mutu isi dan perwajahannya tidak kalah dibanding penerbit profesional. ISBN pun dengan mudah didapatkan.
Kalimantan yang selama ini nyaris tak terdengar, tampil berbagai kelompok penulis dan penerbit Indie. Dreamedia, misalnya. Dengan misi membawa gerakan Kalimantan Selatan Menulis, penerbit ini boleh dikatakan produktif. Mengangkat khasanah lokal. Dengan segmentasi pasar setempat.
Bahkan, ada di antaranya yang dicetak atas pilihan khalayak. Apa yang digagas Dedy Ari Asfar, misalnya. Boleh dikatakan inovatif. Ia mengumpulkan 10 cerpenis Kalbar, menulis dan menerbitkan cerpen dalam bahasa ibu dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.
Jika diperhatikan saksama, inilah paradigma penerbitan di era digital. Cara menentukan isi (buku) bukan lagi oleh penerbit, melainkan oleh khalayak. Dalam bahasa penerbitan modern, disebut “user generated content”.
(rmsp)