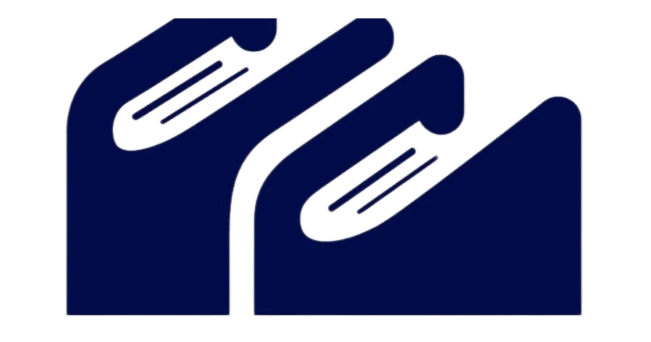Dosen, ketika jadi profesi utama saya rentang tahun 2007-2015. Sering saya undang dosen-tamu, bukan tamu dosen, ke ruang kuliah.
Bukan sekadar nyeling memberikan materi. Agar mahasiswa tidak bosan dan mendapat wawasan berbeda. Namun, agar mereka menimba langsung dari sumber pertama.
Baca https://bibliopedia.id/notes-for-just-like-butterflies/?v=b718adec73e0
Terkait mata kuliah “Literary Journalism” -jurnalistik sastrawi, saya kerap mengundang dosen tamu keren. Salah satunya: Fira Basuki, pesohor ketika itu. Selain model iklan Smartfren, Fira juga novelis yang menghasilkan trilogi novel: Pintu, Atap, Jendela.
Ini rekam jejak Fira waktu saya undang mengisi kuliah.
Fira Basuki, salah satu pendukung jurnalistik sastrawi ketika menjadi dosen tamu mata kuliah yang saya ampu di Fak. Ilmu Komunikasi, Universitas Multimedia Nusantara, Jakarta.
The new journalism, atau jurnalistik sastrawi (bukan jurnalisme sastrawi, sebab tidak pernah dua kata sifat menjadi satu, dan ini salah kaprah!) kini kembali jadi perbincangan hangat. Terutama setelah Molly Blair (2006) merilis disertasinya Putting the Storytelling Back into Stories: Creative Non-fiction in Tertiary Journalism Education, yang membahas mengenai unsur-unsur atau apa yang membentuk senyawa journalism.
Separuh menggugat, Blair menyebut contoh apa jenis tulisan yang mengandung jurnalistik dan mana yang tidak. Lebih lanjut, ia memaparkan secara detail posisi jurnalistik sastrawi dalam konfigurasi media hari ini.
Tulisan ini merupakan akhir dari Bagian pertama buku saya Jurnalatik Sastrawi yang dalam minggu ini siap dirilis oleh Penerbit Salemba Empat.
***
Kendati di Indonesia baru populer dekade 1990-an, sebenarnya sejak kelahirannya pada 1970-an majalah Tempo sudah mempraktikkan jurnalistik sastrawi.
Teknik reportase, ramuan menulis, manajemen, hingga distribusi Tempo yang khas itu merupakan hasil racikan sendiri. Seperti dipaparkan Goenawan Mohamad, Tempo ketika berdiri merupakan satu-satunya media (cetak) yang menulis laporan dengan teknik bercerita.
Baca https://bibliopedia.id/creative-writing-sejarah-dan-perkembangannya-5/?v=b718adec73e0
Kemudian hari, banyak media mengikuti, seakan-akan cara dan teknik penulisan berkisah itu merupakan pakem dan telah lama ada. Padahal, Tempo menemukannya sendiri dengan jatuh bangun dan coba-coba.
Tentang hal itu, Goenawan menulis, “Sebelum ada Tempo, hanya ada dua jenis penulisan dalam koran dan majalah di Indonesia: berita yang lempang (straight news) seperti di koran, atau artikel, seperti “kolom”. Tempo lahir dengan menyajikan cara penulisan yang berbeda sama sekali –yang sekarang jadi pola di penulisan jurnalistik Indonesia (dan sering tidak pada tempatnya dipakai): bagaimana menyusun sebuah berita tentang sebuah kejadian sebagai sebuah cerita pendek.” (Seandainya Saya Wartawan Tempo, 1997: 4).
Mengapa Tempo begitu mudah memulai dan mengadopsi “jurnalistik-baru” ini? Agaknya, itu karena para awak Tempo (jurnalis, fotografer, hingga jajaran pimpinannya) banyak yang juga sastrawan.
Fira Basuki, Ahmadun Y. Herfanda, dan Ayu Utami: jurnalis-sastrawan yang turut mewarnai dan menyosialisasikan jurnalistik sastrawi. Jadi, saya wajib membawa mahasiswa langsung ke sumber pertamanya.
Otomatis, mereka merangkai dan menulis fakta terpengaruh gaya sastra juga, menggunakan teknik serta cermat menerapkan elemen-elemen sastra dalam penulisan dan laporan jurnalistik mereka. Sebagai contoh, Goenawan Mohamad, Putu Wijaya, Eka Budianta, Fikri Jufri, Lelila Chudori, dan Bondan Winarno. Ditambah kolumnis yang juga sastrawan seperti Ehma Ainun Najib, Parakitri T. Simbolon, Christianto Wibisono, Jakob Sumardjo, Korrie Layun Rampan, dan Taufik Ismail.
Masih ada jurnalis-sastrawan yang pada awal kemunculan jurnalistik sastrawi dekade 80-an, turut ambil bagian secara aktif memberikan warna pada jurnalistik sastrawi khas Indonesia.
Sebagai contoh, Remy Sylado yang bekerja sebagai redaktur majalah Aktuil, Korrie Layun Rampan di majalah Sarinah, Marianne Katoppo yang bekerja di PSH Grup, Julius Siyaranamual yang bekerja di Harian Surya, Titie Said yang bekerja pada majalah Kartini, Yudhistira ANM Massardi yang bekerja pada beberapa majalah mingguan umum, Seno Gumira Ajidarma bekerja di Jakarta-Jakarta, dan Veven Wardhana yang bekerja di tabloid Citra.
Tradisi jurnalistik sastrawi para pelopor itu, diteruskan generasi berikut, yang juga jurnalis-sastrawan. Para jurnalis-sastrawan itu sukses, terbukti dari penghargaan tingkat nasional maupun internasional yang mereka raih.
Namun, lepas dari pengakuan itu, karya-karya mereka sanggup “menyihir” pembaca dan menjadi tulisan yang kehadirannya senantiasa ditunggu-tunggu. Sebagai contoh, Ahmadun Y. Herfanda yang bekerja di Republika, Ayu Utami di Matra dan beberapa majalah lain, dan Fira Basuki yang bekerja di majalah Cosmopolitan.
Fira Basuki, Ahmadun Y. Herfanda, dan Ayu Utami: jurnalis-sastrawan yang turut mewarnai dan menyosialisasikan jurnalistik sastrawi. Selanjutnya, para awak jurnal Pantau juga gencar menyosialiasikan jurnalistik sastrawi, dengan memberikan pelatihan bagi sejumlah jurnalis baik pada tataran lokal maupun nasional.
Baru akhir-akhir ini, perguruan tinggi turut aktif ambil bagian di dalam pengembangan dan inseminasi jurnalistik sastrawi, namun belum secara holistik sebagai sebuah kajian ilmu seperti di luar negeri.
Hal ini tampak dari beberapa buku dan substansi materi perkuliahan yang masih berpandangan lama, menganggap bahwa jurnalistik sastra, atau feature, ialah “pelengkap” dari hard news.
Padahal, hakikat jurnalistik sastra tidaklah demikian, ia substansi dengan genre yang memunyai tempat dan daya pikat tersendiri dalam konfigurasi jurnalistik modern. Bahkan, karena daya pikatnya, jurnalistik sastra dapat bersaing dengan berita-berita keras dan kecepatan media elektronik di dalam men-deliver informasi kepada khalayak.
Para jurnalis-sastrawan dan sastrawan-penulis itu, sadar atau tidak, telah membawa warna, nuansa, dan gaya baru jurnalistik yang di Inggris, Amerika, dan Australia memang sudah lama dipraktikkan. Sebagaimana dicatat Blair (op.cit.: 22)
The first major example of the crossover between the literary and the journalistic occurred in 1846 when the London Daily News was published with Charles Dickens as founding editor. In Australia, in the mid 1860s, newspapers included in their weekly publications serialised novels and other literary reading matter (Morrison, 1993, p.64). In the late 1880s The Bulletin began to publish regularly the works of writers such as Henry Lawson and Banjo Patterson (Australian Government Department of Communications p.1). In 1923 the weekly news magazine Time was launched in America, followed in 1925 by the New Yorker and in 1933 by Life, Sport Illustrated and Fortune (Stephens, 1997, p.xxi). In Australia, what would become the world’s highest circulating magazine per capita, Australian Women’s Weekly, also emerged in 1933. While this publication is well known today as a monthly magazine, the Weekly was in newspaper format at its inception (“History: The Australian Women’s Weekly”, 2004, p.1).
Apabila dibandingkan dengan Amerika, Inggris, dan Australia yang sudah lebih dulu mempraktikkan jurnalistik sastrawi, kondisi di Indonesia juga kurang lebih sama. Persilangan antara jurnalistik dan sastra pada era 1970-an juga muncul melalui majalah Tempo dan majalah bulanan Intisari dan Trubus. Gaya penulisan, elemen-elemen, maupun struktur jurnalistik di majalah-majalah tersebut mengandung dan menerapkan teknik penulisan sastra.
Mengapa terjadi persilangan jurnalistik dan sastra pada media yang disebutkan di atas? Jawabannya tentu karena ideologi dan pengaruh dari warna kepenulisan yang dibawakan oleh para sastrawan yang bekerja di media tersebut.
Sastra, Jurnalistik, dan Masyarakat
Jurnalistik sastra dan elemen-elemenya, akan terasa mudah dimengerti, apabila membaca lebih dulu karya sastra-karya sastra bermutu yang berkonteks sosial budaya.
Itu sebabnya, mahasiswa ditugaskan membaca karya sastra bermutu.
Selain untuk memerkaya wawasan dan pengalaman batin, juga melalui bacaan seseorang menemukan gaya dan dapat memetik teknik dan trik penulis lain merangkai fakta menjadi karya jurnalistik. Dengan mengemulasi bacaan-bacaan bermutu, seseorang memeroleh sesuatu yang bermutu pula.
Di sini menjadi genap apa yang dikatakan Lord Bryon, “A drop of ink may make a million think.” Jika diterjemahkan ke situasi kondisi sekarang, kata-kata bijak itu berarti: bacaan bermutu memberi sejuta inspirasi.
Pendidikan jurnalistik sebaiknya didesain sedemikian rupa, sehingga memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat. Dengan menguasai keterampilan menulis genre tulisan non-fiksi kreatif, yang dasar keilmuan dan keterampilannya ialah sastra, seorang jurnalis memunyai masa depan yang cerah.
Baca https://bibliopedia.id/makan-buku-3/?v=b718adec73e0
Sesuai dengan sembilan elemen jurnalistik Bill Kovach dan Tom Rosentiel, yang menegaskan bahwa kerja jurnalistik terhubung dengan warga, maka sejak dini pendidikan calon jurnalis di perguruan tinggi diarahkan pada (kebutuhan) masyarakat…*)