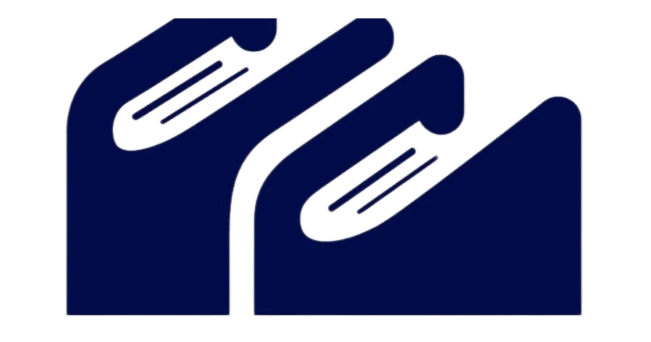Di balik peribahasa/ tacit knowledge/ adagium suatu kaum, ada: filosofi, sekaligus: entografi. Dalam proses ON di Google-books dalam senarai publikasi internasional Penerbit Lembaga Literasi Dayak (LLD).
***
Yang lama. Sekaligus menyita waktu serta meguras pikiran dan tenaga, adalah menemukan metodologi serta menyusun sistematika buku seperti ini.
Lama berkanjang di penyusunan kamus (saya ketua tim penerjemah Kamus Visual), leksikon, dan dunia creative writing, saya memutuskan metodologi penyusunan dan penulisan peribahasa ini sbb: secara alfabetis mengurutkan apa yang menjadi lema/ entri, misalnya peribahasa:
“Ngungus buah tongan: yang berarti:
Menyedot buah jari. Makan dalam keadaan tanpa sayur atau lauk-pauk – masuk ke dalam lema T -tongan, tangan.
Apa masih perlu diantar-antar lagi? Bukankah dari judulnya, orang Pembaca. sudah merasa sangat gamblang dengan maksud dan tujuan buku ini?
Demikian saya menjawab, ketika penulis buku ini meminta supaya naskah bukunya diantar ke hadapan Sidang Pembaca.
Setelah ditimbang-timbang, pada akhirnya, saya menyerah juga. Betul bahwa judul mencerminkan esensi suatu buku. Namun, khususnya dalam konteks buku ini, sidang pembaca belum semua mengetahui latar, suasana jiwa, serta konteks di mana dan bagaimana peribahasa yang diikat jumlahnya dalam bilangan keramat 101 ini, terjadi.
Bagi orang Dayak, ia bukan sekadar angka. Namun, di baliknya ada: makna. Angka 101 ada bulatan, yang dipagari kiri kanan dengan simbol angka 1. Melambangkan adat budaya serta nilai tradisi Dayak Jangkang yang harus dijaga, diperihara, meski langit runtuh dan bumi berguncang oleh dinamika zaman.
Dalam khasanah sejarah filsafat di tanah Yunani, sejauh yang saya baca dan pelajari, peribahasa melalui mitologi dan syair-syair –katakanlah seperti Illiad dan Odyssey, juga sarat dengan peribahasa. Di dalamnya, adalah hasil “perasan santan”, yang ampasnya telah dibuang. Ia daging semua. Bernas. Berisi saripati tacit knowledge suatu kaum, klan, dan suku bangsa yang dihidupi selama beratus, bahkan beribu tahun lamanya.
Kita mengetahui bahwa di dalam proses kelahiran dan konfigurasi ilmu pengetahuan, tacit knowledge itu adalah 95% pengetahuan dan kebajikan manusia. Sisanya, yang tertulis dan terdata, hanya 5%.
Pengetahuan tacit ini yang kental di kalangan suau etnis yang masih hidup dalam adat budaya tradisional. Dari lata Latin “tacere”, orang ketiga tunggalnya “tacit”, per makna kamus berarti: diam, tidak berbicara (Kamus Latin Indonesia, 1969: 847).
Yang dimaksudkan, sudah barang tentu, bukan diam dalam arti harfiah, kelu, atau tidak berbicara sama sekali. Pengetahuan tacit adalah pengetahuan yang didapat bukan di bangku sekolah atau kuliah, dari proses belajar-mengajar formal antara guru-murid.
Akan tetapi, pengetahuan tacit yang didapat seorang pembelajar-serius melalui serangkaian: pengalaman, pemikiran, kompetensi, dan komitmen. Diolah sedemikian rupa, melalui proses dialektika layaknya ilmu dan teori, sedemikian rupa menjadi pengetahuan dan kompetensi yang bersistem dan bermetodologi.
Dapat dikatakan, seorang yang memiliki pengetahuan tacit bahkan sudah sampai pada aras menemukan dan membangun teorinya sendiri.
Muncul dalam 4 keungulan utama, Pengetahuan tacit ini terdiri atas: pengalaman, pemikiran, kompensi, dan komitmen. Dalam 101 peribahasa Dayak Jangkang ini, kita menemukan semuanya itu!
***
Pada akhirnya, agar konteks peribahasa ini semakin menemukan tempatnya yang pas, perlu dipaparkan: Siapa Dayak Jangkang?
Dalam Wikipedia, yang saya susun narasinya, teridentifikasi dan ternarasikan dengan jelas:https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Dayak_Jangkang
Maka kiranya hal itu tidak perlu diulang lagi di sini. Bahkan, ada sebuah monograf yang dalam lagi detail, yakni Dayak Djongkang 2010. yang memenangkan hibah buku teks DP2-M, Kemendikbud.
Di sini cukup disinggung sekilas saja.